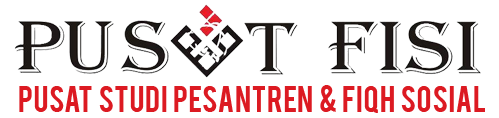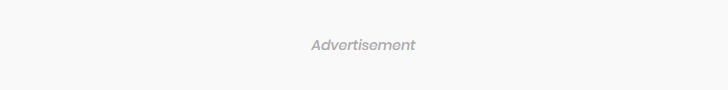Oleh: Umdah El Baroroh
Keberhasilan Nahdhtaul Ulama’ (NU) pada muktamar ke-33 di Jombang lalu dalam merumuskan metode istimbath hukum layak mendapat apresiasi. Pada komisi Bahtsul Masail Maudhuiyyah, NU berhasil merumuskan metode istimbat hukum yang berpedoman pada konsep bayani, istishlahi dan maqashidi. Penjabaran dari model istimbath ini ditegaskan oleh salah satu tim perumus dalam lembaga Bahtsul Masail ini, DR. Abdul Moqsith Ghazali, sebagai model istimbath yang tidak saja bergantung pada bunyi tekstual nash. Keberadaan teks atau nash tetap diakui sebagai pendekatan utama yang tidak mungkin diabaikan. Tetapi pada kesempatan lain, kita juga harus mengembangkan pemahaman bahwa teks tidaklah terbatas pada teks yang tertulis. Namun juga yang terlihat atau yang terdengar. Oleh karena itu kita membutuhkan pemahaman teradap konsep istishlah dalam hukum. Istishlah atau menemukan kemaslahatan hukum pada dasarnya adalah upaya merealisasikan maqashid atau tujuan hukum.
Selama ini yang sering menjadi perdebatan sengit dan menakutkan beberapa kalangan ulama’ fiqh adalah upaya penentuan mashlahah itu sendiri. Meskipun mashlahah telah disepakati sebagai tujuan hukum, tetapi dalam pengukurannya, seringkali terjadi perdebatan yang cukup sengit. Beberapa ulama’, yang terwakili dalam kelompok ‘nashirus sunnah’ tidak mempunyai keberanian untuk menjadikan mashlahah sebagai dalil hukum. Hal itu berbeda dengan kelompok malikiyah yang memberanikan diri untuk mengakui mashlahah ini sebagai dalil hukum.
Di Indonesia sendiri, perdebatan tentang penentuan hukum berbasis mashlahah seringkali berujung pada perdebatan seru. Hal itu dipicu oleh ketidakberanian dalam menentukan ukuran kemaslahatan yang selalu harus dipatok pada kemaslahatan umum (mahslahah ammah). Standar keumuman maslahah inilah yang seringkali blunder bagi pembuat hukum. Dalam kehidupan modern yang kompleks tentu tidak mudah dalam menentukan kemaslahatan umum. Apalagi di negeri majemuk seperti Indonesia. Hal ini yang sering membuat persoalan hukum harus berakhir ‘mauquf’.
Terobosan baru yang dilakukan oleh NU dalam muktamar ke-33 ini pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1992 pada Munas Lampung yang telah merumuskan metode istimbath hukum bagi kalangan ulama NU. Tetapi keputusan tersebut mandeg, bahkan tidak banyak diketahui orang karena dianggap kurang ‘mu’tabar’. Tetapi membiarkan masalah di masyarakat semakin banyak yang mauquf juga mengakibatkan ‘ilgha’ al ahkam’. Keberanian NU untuk membuat rumusan istimbath itu saya maknai sebagai kepedulian NU terhadap nasib umat yang setiap hari menghadapi permasalahan yang bermacam-macam.
Selain kepedulian terhadap umat, rumusan hasil Bahtsul Masail ini juga semakin meneguhkan kepada masyarakat tentang pentingnya kehadiran fiqh sosial dalam kehidupan berfiqh masyarakat. Pendekatan istimbath hukum yang tidak saja menitikberatkan pada pendekatan teks atau pendekatan keshahihan vertical dengan standar ketuhanan, perlu segera dipromosikan di masyarakat luas, terutama di lingkungan akademisi dan pesantren.
Kiai Sahal dalam Nuansa Fiqh Sosial, pada awal tahun 90-an telah mengkritik praktek fiqh yang lebih menitikberatkan kepentingan Tuhan, dibanding kepentingan umat manusia. Dalam buku itu kiai Sahal mengingatkan kembali kepada kita bahwa syari’ah pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, bukan Tuhan. Tetapi kita seringkali ketakutan untuk mendefinisikan kemaslahatan kita sendiri. Hal inilah yang sering menghambat hukum dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu kiai Sahal menganjurkan adanya perubahan arah pada pendekatan fiqh. Fiqh harus lebih bisa melihat kemaslahatan manusia. Fiqh harus mampu memecahkan masalah manusia dengan berbasis kemaslahatan manusai, bukan Tuhan. Pendekatan itulah yang dideklarasikan oleh Kiai Sahal sebagai Fiqh Sosial.
Nah, keputusan dari Munas NU maupun Bahsul Masail NU pada Muktamar ke-33 Jombang ini merupakan penegasan tentang pentingnya meneguhkan kembali aplikasi fiqh sosial dalam mendekati kasus hukum. Model berfiqh hari ini adalah berfiqh sosial. Kita harus sudah berani beranjak dari ketakutan dan keraguan dalam menjawab masalah waqi’iyah di lingkungan masyarakat hanya karena keterbatasan teks. Kita harus sudah mengamalkan makna teks secara kontekstual dengan metode yang juga kontekstual. Wallahu a’lam bisshawab.
Recent Posts
3/recent/post-list
Berita FISI
3/Berita/post-list
Copyright ©
FISI IPMAFA